
Jika kamu menemukan mesin waktu, apa yang akan kamu lakukan? Dan, jika kamu punya kesempatan kembali ke masa lalu, ke masa mana kamu akan kembali?
Ini bukan pertanyaan dalam benak saya saja. Simak, tiga film yang bercerita tentang mesin waktu yang tengah tayang di layar lebar: “Shreek 3: Forever After”, “Prince of Persia: The Sands of Time”, dan “Hot Tube Time Machine”. Saya sudah nonton dua judul pertama. Dalam salah satu mata kuliah ilmu komunikasi, saya mengetahui film itu merepresentasikan fenomena yang sebenarnya terjadi.
Kenapa orang ingin kembali ke masa lalu?
*
Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Jakarta. Pertengahan Mei 2010.
Saya buru-buru melompat ke dalam taksi segera setelah mobil itu menepi. “Proklamasi, Pak. Kita lewat Manggarai,” kata saya.
Lalu saya menyenderkan punggung. Sejenak memejamkan mata sambil mengingat hal-hal yang harus saya lakukan hari ini. Sampai suara “sember” sang sopir memecah keheningan.
“Di mana-mana jalan macet, Neng,” ucapnya. “Banyak demo.”
“Ohya?” Alis saya berkerut. Berusaha keras mengingat ini hari apa. “Oh, sepuluh tahun lalu kan Soeharto lengser,” jawab saya ketika berhasil mengingat.
“Ah, zaman sekarang ini memang nggak enak. Apa-apa susah. Cari makan susah. Cari pekerjaan susah. Lebih enak zaman Soeharto dulu, kan semuanya makmur,” katanya dengan nada dongkol.
Dahi saya langsung berkerut. Pikiran saya menolak. Tapi saya memilih mendengarkan pendapatnya, toh semua orang berhak memiliki pendapat yang berbeda.
“Coba, apa yang dihasilkan sekarang. Jalan tol, gedung-gedung, yang membangun kan Soeharto. Sekarang orang miskin bertambah, cari duit susah,” keluhnya bertubi-tubi.
Sebenarnya dalam pikiran saya tersedia argumentasi: tanpa bermaksud membela pemerintah sekarang, tentu saja jumlah orang miskin bertambah. Lha wong tiap tahun jumlah penduduk bertambah.
Urbanisasi makin kencang karena kesejahteraan tidak merata di seluruh daerah. Melihat tipe orangnya, percuma diajak debat. Dia sudah keukeh dengan pendapatnya. Saya memilih diam, dengan pemikiran, nanti toh kalau sudah capek bicara dia bakal diam. Mungkin dia lelah dengan beban ekonominya. Orang tipe begini hanya perlu didengarkan. Tidak perlu lagi diceramahi. Dia capek menanggung kehidupan.
Tapi dia terus saja bicara dan mengagung-agungkan masa lalu.
“Pak,” akhirnya saya bicara, dengan nada lembut. “Tidak sepenuhnya zaman dulu itu enak. Zaman itu banyak orang hilang misterius, tahu-tahu ditemukan sudah jadi mayat. Banyak yang diculik, dan tidak kembali. Jalan tol itu, yang bangun juga masih dinasti, yang masuk kocek keluarganya sendiri. Sebenarnya, tiap zaman itu ada pahit manisnya juga. Sama saja seperti sekarang,” tutur saya.
Bukannya dia menjadi semakin tenang, kedongkolannya semakin memuncak. Dia semakin memuji-muji pemerintahan orde baru yang menurut dia sukses dengan kemakmurannya. Ah, batin saya, andai dia tahu betapa di daerah terpencil dan pedalaman luar sana, pada masa itu penduduk banyak menjerit kelaparan dan kekeringan tanpa air. Dan jika zaman sekarang ini seperti pemerintahan orde baru, orang-orang dengan profesi seperti saya—wartawan—tak akan hidup tenang. Bisa diteror kapan pun, atau diancam pembunuhan bahkan menghilang.
Kenapa sih, orang ini “ngebet” sekali ingin kembali ke masa lalu?
*
Siapa sih, yang tidak pernah ingin kembali ke masa lalu? Masa-masa sulit, selalu membuat kita menoleh ke belakang, saat situasi masih begitu nyaman.
Saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah hidup yang tidak kekurangan. Tidak usah mikir hari ini bakal makan apa, semuanya tersedia. Saya tinggal menadahkan tangan dan uang itu bakal mengalir ke kocek saya. Mobil dan sopir semua tersedia. Mau makan dan minum saya tinggal panggil pembantu di rumah, dan mereka buru-buru menyediakannya di meja makan saya. Arloji merek terbaru. Mobil keluaran terbaru. Saat parabola masih menjadi barang mewah dan langka, di rumah saya payung besi terbalik raksasa itu sudah nongkrong. Semua orang di sekolah mengenal siapa saya dan keluarga saya.
Benar pepatah bilang, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kamu di atas, dan satu waktu kamu bakal di bawah. Krisis ekonomi datang dan menghajar semuanya. Bahkan rumah pun saya tidak punya. Tinggal harus mengontrak dari satu rumah ke rumah lain. Impian untuk sekolah di luar negeri pupus sudah. Saat-saat itu, betapa saya merutuki hidup.
Kesulitan yang datang bertubi-tubi memang bisa membuatmu mempertanyakan makna hidup dan siapa Tuhan. Saya mengerti rasanya. Betapa tidak nyaman jika kamu pernah memiliki kenyamanan dan semuanya itu tiba-tiba hilang begitu saja. Itu menyakitkan.
Saat itu, saya begitu ingin mengubah sejarah. Saya ingin kembali ke masa lalu.
Pertanyaan saya: “Tuhan, jika Kau memang ada, kenapa kau biarkan aku menderita?”
Tanpa saya sadar, hidup tengah memberikan bab pelajaran baru dalam catatan perjalanan kehidupan saya. Saya belajar hidup sederhana. Saya belajar rendah hati. Saya belajar naik angkutan kota. Saya bicara pada pedagang kaki lima dan pengemis. Saya mengenali siapa orang-orang yang tetap bersama saya ketika kehidupan saya memasuki masa kegelapannya. Saya menemukan teman-teman sejati saya. Orang-orang yang menarik saya dari dalam kegelapan dan membuat saya kembali mencintai kehidupan.
“Segala sesuatu yang kamu alami tak akan pernah melebihi kekuatanmu,” kata seorang teman di Jogja.
“Lalu kenapa Tuhan diam saja ketika saya menderita?” saya bertanya.
“Dia mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk membentukmu menjadi sesuatu yang Dia siapkan. Suatu saat, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang kamu alami. Dan kamu akan membagi pengalaman hidupmu pada mereka,” kata teman saya.
Milikilah harapan. Harapanlah yang membuat kamu hidup, bukan hidup itu sendiri. Saat kamu berjalan bersama Tuhan, kamu akan selalu menemukan harapan itu.
Teman saya itu benar. Saya bisa melaluinya. Hidup terus berjalan. Perubahan terjadi. Tantangan hidup selalu ada, tapi saya tahu di mana kekuatan sejati saya.
Saya bisa memilih, hidup dengan hati yang ditawan masa lalu, atau bergerak menerobos masa depan dengan harapan. Pikiran adalah mesin waktu itu. Saya punya pilihan menekan tombol off untuk melompat ke masa lalu. Dan menekan tombol on untuk menjalani hidup sekarang.
Napas saya masih berhembus. Jantung saya masih berdetak. Sampai saat ini. Saya tidak mau kembali pada masa lalu saya. Sama sekali.
*
“Belok mana, Neng? Kiri atau kanan?” tanya sopir dengan suara “sember” itu.
“Kiri Pak, kalau kiri itu Proklamasi. Kalau ke kanan itu Kramat Raya,” jawabku. Rupanya, dia berhenti mengoceh karena aku diam dan tidak menanggapi omongannya.
Taksi itu kuminta menepi di sebelah kiri, sebuah bangunan tingkat yang letaknya tak jauh dari Toko Buku Immanuel.
“Ini kantor apa, Mbak?” tanyanya.
“Oh, ini kantor Tempo. Majalah Tempo.” Aku melirik argo taksi, Rp 12.500. Aku membuka dompet dan mengambil uang dua puluh ribu.
“Majalah Tempo? Oh... Tempo, yang pernah dibredel itu? Ada yang namanya Bambang Harimurti itu?” suaranya seperti tercekat. Sepertinya dia mulai sadar, sepanjang perjalanan dia salah bicara.
“Iya, betul Pak,” ucapku sambil menyerahkan uang. “Tidak usah kembaliannya, buat Bapak saja, semoga hari Bapak menyenangkan,” lanjutku sambil tersenyum.
Bruk. Kututup pintu taksi. Berjalan menuju pintu masuk kantor yang terbuat dari kaca. Dari pantulan kaca, kulihat taksi itu belum juga beranjak. Bahkan sampai aku masuk dan menoleh ke luar, taksi itu masih belum beranjak. Sampai beberapa detik kutunggu, sedan itu baru berjalan.
Entah apa yang ia pikirkan.
***
Nieke Indrietta
Jakarta, Minggu, 6 Juni 2010
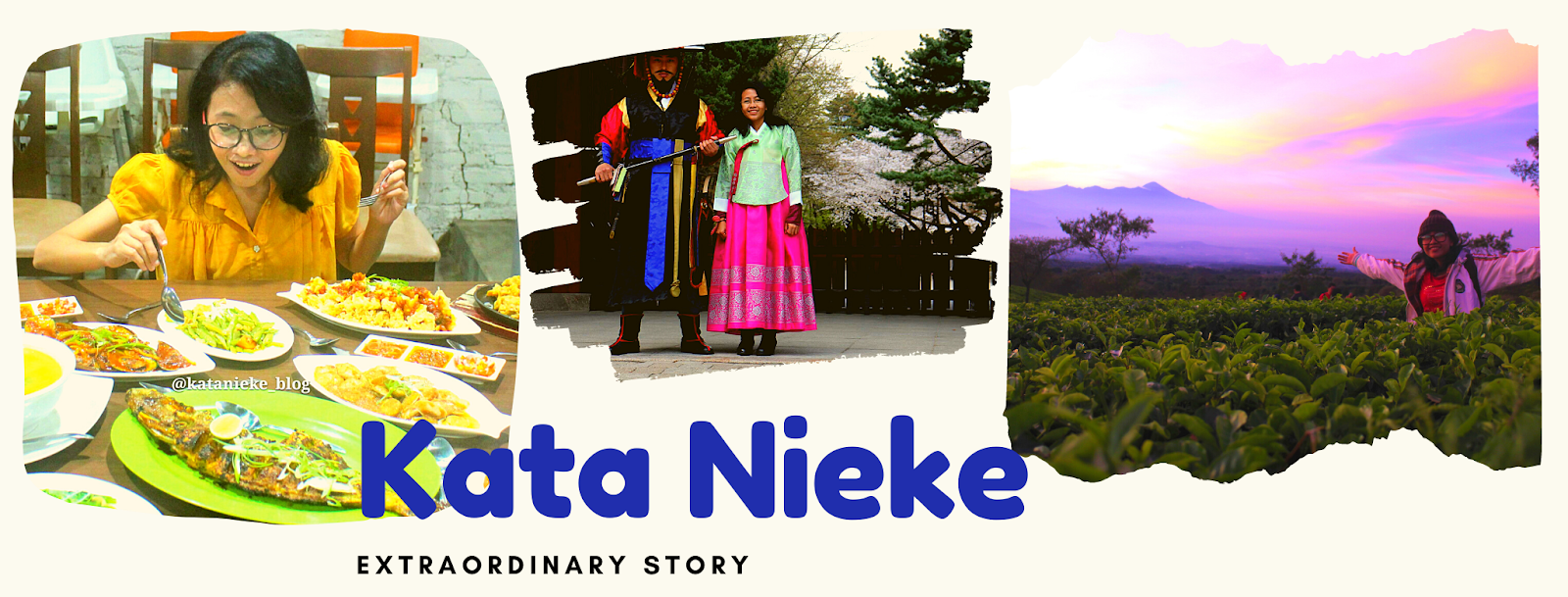




Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Hi... terima kasih sudah mampir dan membaca blog saya. Mohon berkomentar dengan sopan, tidak meninggalkan spam, tidak menggunakan LINK HIDUP di kolom komen. Sebelum berkomentar, mohon cek, apakah Anda sudah memiliki profil di akun Anda. Profil tanpa nama atau unknown profil tidak akan diterima berkomentar. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya tidak gunakan akun anonim.
Salam.